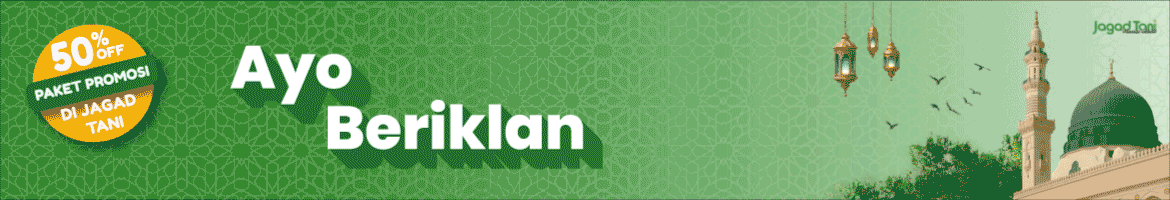Jagad Tani - Reforma agraria di sektor kehutanan bukan hanya soal redistribusi (penyaluran ulang) lahan, tetapi juga soal menata kembali keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan lingkungan.
Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut), sejak 2016 hingga Oktober 2025, realisasi penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan telah mencapai 3,04 juta hektare, atau sekitar 73% dari target nasional sebesar 4,1 juta hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,58 juta hektare merupakan penyelesaian untuk permukiman, kawasan transmigrasi, fasilitas sosial dan umum, serta lahan garapan masyarakat yang telah lama diusahakan.
Capaian ini tentu menjadi langkah maju dalam menghadirkan keadilan agraria, namun juga menjadi pengingat bahwa perjalanan masih panjang. Melalui program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), pemerintah harus bisa memastikan akses lahan yang adil bagi masyarakat tanpa harus mengorbankan fungsi ekologis (lingkungan) hutan.
Tantangannya justru terletak pada keberpihakan hukum dan implementasi (penerapan) di lapangan, apakah kebijakan ini benar-benar berpihak pada rakyat yang telah lama hidup dan bergantung pada kawasan hutan.
Baca juga: Pesisir Sulawesi Tenggara Tanam 1.000 Bibit Mangrove
Persoalan penguasaan lahan di kawasan hutan yang sudah berlangsung puluhan tahun juga memerlukan landasan hukum yang kuat dan konsisten. Reforma agraria tidak boleh berhenti pada redistribusi lahan saja, tetapi juga harus menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi, peningkatan produktivitas, serta konservasi Sumber Daya Alam (SDA). Hal ini telah diatur melalui berbagai regulasi, di antaranya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021, Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021, dan Perpres Nomor 62 Tahun 2023, yang menegaskan pentingnya keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Secara sosial, pelaksanaan PPTPKH setidaknya sudah menurunkan intensitas konflik agraria dan mengubah wilayah rawan sengketa menjadi desa produktif. Namun, kenyataan di lapangan belum sepenuhnya ideal. Kasus-kasus seperti konflik agraria di Indramayu yang belum terselesaikan menjadi pengingat bahwa reforma agraria memerlukan pengawasan dan komitmen lintas sektor. Serikat Petani Indonesia (SPI) Indramayu bahkan turun ke jalan pada saat peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2025 dan Hari Pangan Sedunia, untuk menuntut kejelasan soal penyelesaian konflik yang telah lama mereka hadapi.
Dari sisi ekologis, penerapan sistem agroforestry dan ekonomi hijau menjadi strategi penting dalam menjaga tutupan hutan sekaligus membuka ruang bagi kegiatan produktif yang berkelanjutan. Namun, tanpa pengawasan ketat dan transparansi, kebijakan tersebut bisa disalahgunakan. Sistem perencanaan spasial berbasis Peta Indikatif PPTPKH yang memanfaatkan teknologi citra satelit, drone, serta masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan menjadi langkah penting menuju tata kelola kehutanan yang lebih akuntabel (bertanggung jawab).
Pada akhirnya, PPTPKH dan TORA bukan hanya dijadikan sebagai program teknis, tetapi juga harus menjadi gerakan sosial nasional dalam menegakkan nilai keadilan sosial, ketahanan pangan, dan pelestarian lingkungan. Dengan realisasi nyata serta berdampak bagi masyarakat, kebijakan ini harus menjadi bukti bahwa negara hadir di tengah rakyatnya, demi menata hutan untuk kehidupan. Sebab dari hutan dan lahan yang tertata, ruang ekonomi kerakyatan bisa tumbuh.